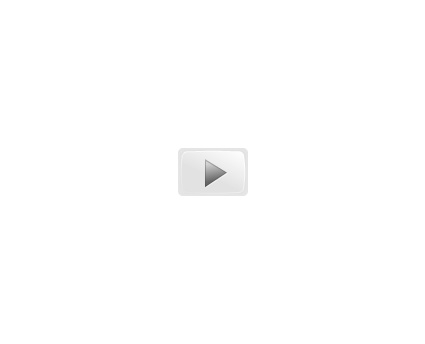ISTISHHAB
الاستصحاب

Oleh:
AFLAH SHORIH
08110010
TARBIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2008/2009
ISTISHHAB
Definisi Istishhab
Istishhab secara bahasa artinya “meminta bersahabatan atau membandingkan dan mendekatkannya”
Istishhab secara bahasa artinya “meminta bersahabatan atau membandingkan dan mendekatkannya”
Adapun secara terminologi beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama Ushul Fiqih, diantaranya adalah:
1. Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(Istishhab) adalah penetapan (keberlakukan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut)
2. Sementara al-Qarafy (w. 486H) seorang ulama Malikiyah mendefinisikan istishhab sebagai “keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang.
1. Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(Istishhab) adalah penetapan (keberlakukan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut)
2. Sementara al-Qarafy (w. 486H) seorang ulama Malikiyah mendefinisikan istishhab sebagai “keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang.
Contoh :
Dalam sebuah perkawina, setelah berlangsungnya akad nikah antara seorang perjaka dengan seorang perawan dan setelah berlangsungnya hubungan suami istri, suami mengatakan bahwa istrinya tidak perawan lagi. Tuduhan suami itu tidak dapat dibenarkan, kecuali ia dapat mengemukakan bukti-bukti yang sah dan kuat, karena seorang perawan pada dasarnya belum melakukan hubungan suami istri.oleh karena itu tuduhan dari suami bahawa ia tidak perawan lagi ketika sudah kawin.
Kaidah-kaidah istishhab
- Al-ashl baqa’ ma ala ma kana, hattayusbita ma yughyyirah.
الا صل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره
Maksudnya , pada dasrnya seluruh hukum yang sudah dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukan hukum itu tidak berlaku lagi. Contohnya :
Orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan wakaf, karena mereka belum di pastikan hidup. Sebaliknya harta mereka belum bisa di bagi pada ahli warinya sampai keadaan orang itu benar-benar wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya seseorang
2. Al-ashl fi al-arsyya al-ibadah
الاصل فى الاشياء الاباحة
Maksudnya, pada dararnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh akad/transaksi dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukan hukumnya batal, sebagaiman juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara’ yang melarangnya , maka hukumnya adalah boleh.
- Al-yaqin la yuzal bil al-syak.
اليقين لايزال بالشك
Maksudnya, suatu keyakinan tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan.. contohnya.:
apabila seseorang makan saur di akhir malam, dia tidak mengetahui sudah terbit fajar apa belum, dalam kasus seperti ini, maka seharusnya dilanjutkan terus dan puasanya sah, karena keyakinan bahwa hari masih malam, lebih kuat dibandingkan keraguan bahwa fajar telah terbit
- Al-ashl fi al-dzimmah al-baraah min al-takalif wa al-huquq
الاصل فى الذمة البراءة من التكاليف والحقوق
maksudnya, pada dasrnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggungjawab seseorang. Oleh sebab itu, sesorang tergugat dalam kasus apa pun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah.
Permasalahan Istishhab dalam Persoalan-persoalan Furu’iyah
Berikut ini adalah beberapa contoh persoalan furu’iyah yang termasuk dalam kategori tersebut:
Pewarisan Orang yang Hilang (al-Mafqud)
Orang yang hilang (al-mafqud) adalah orang yang menghilang dari keluarganya hingga beberapa waktu lamanya, dimana tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah ia masih hidup atau sudah mati.
Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat antara memvonis ia masih hidup sehingga peninggalannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya dan ia tetap berhak mendapatkan warisan jika ada kerabatnya yang meninggal saat kehilangannya; dan memvonis ia telah meninggal sehingga peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:
Pewarisan Orang yang Hilang (al-Mafqud)
Orang yang hilang (al-mafqud) adalah orang yang menghilang dari keluarganya hingga beberapa waktu lamanya, dimana tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah ia masih hidup atau sudah mati.
Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat antara memvonis ia masih hidup sehingga peninggalannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya dan ia tetap berhak mendapatkan warisan jika ada kerabatnya yang meninggal saat kehilangannya; dan memvonis ia telah meninggal sehingga peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:
Pendapat pertama, bahwa ia tetap dianggap hidup baik untuk urusan yang terkait dengan dirinya maupun yang terkait dengan orang lain. Karena itu semua hukum yang berlaku untuk orang yang masih hidup tetap diberlakukan padanya; hartanya tidak diwariskan, istrinya tidak boleh dinikahi, dan wadi’ah yang ia titipkan pada orang lain tidak boleh diambil. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan al-Syafi’i.
Hujjah mereka adalah bahwa orang yang hilang itu sebelum ia hilang ia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Karena itu hukum ini wajib diistishhabkan hingga sekarang sampai ada bukti yang mengubah hukum tersebut.
Hujjah mereka adalah bahwa orang yang hilang itu sebelum ia hilang ia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Karena itu hukum ini wajib diistishhabkan hingga sekarang sampai ada bukti yang mengubah hukum tersebut.
Pendapat kedua, ia dianggap hidup terkait dengan hak dirinya sendiri. Pendapat ini dilandaskan pada pandangan bahwa istishhab hanya dapat digunakan untuk mendukung hukum yang telah ada sebelumnya, tapi bukan untuk menetapkan hukum baru.
Pendapat ketiga, ia dianggap hidup baik terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain selama 4 tahun sejak hilangnya. Jika 4 tahun telah berlalu, maka ia dianggap telah meninggal terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain; hartanya dibagi, ia tidak lagi mewarisi dari kerabatnya yang meninggal dan istrinya dapat dinikahi. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
Alasan pembatasan jangka waktu 4 tahun adalah pengqiyasan kepada jika ia meninggalkan istrinya selama 4 tahun, dimana –menurut pendapat ini- jika ia meninggalkan istrinya selama itu, maka hakim dapat memisahkan keduanya dan istrinya dapat dinikahi setelah masa iddah sejak pemisahan itu berakhir.
Alasan pembatasan jangka waktu 4 tahun adalah pengqiyasan kepada jika ia meninggalkan istrinya selama 4 tahun, dimana –menurut pendapat ini- jika ia meninggalkan istrinya selama itu, maka hakim dapat memisahkan keduanya dan istrinya dapat dinikahi setelah masa iddah sejak pemisahan itu berakhir.
Berwudhu Karena Apa yang Keluar Dari Selain “2 Jalan”
Semua ulama telah berijma’ bahwa segala sesuatu yang keluar melalui “2 jalan” (qubul dan dubur) itu membatalkan thaharah seseorang. Namun bagaimana dengan najis yang keluar tidak melalui kedua jalan tersebut? Apakah ia juga membatalkan thaharah seseorang atau tidak?
Dalam kasus ini, ada beberapa pendapat yang dipegangi oleh para ulama:
Semua ulama telah berijma’ bahwa segala sesuatu yang keluar melalui “2 jalan” (qubul dan dubur) itu membatalkan thaharah seseorang. Namun bagaimana dengan najis yang keluar tidak melalui kedua jalan tersebut? Apakah ia juga membatalkan thaharah seseorang atau tidak?
Dalam kasus ini, ada beberapa pendapat yang dipegangi oleh para ulama:
Pendapat pertama, bahwa hal itu membatalkan thaharahnya, sedikit ataupun banyaknya yang keluar. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan al-Syafi’i.
Hujjah mereka adalah istishhab, yaitu bahwa hukum asalnya hal itu tidak membatalkan, maka ia tetap diberlakukan hingga ada dalil yang menunjukkan selain itu.
Hujjah mereka adalah istishhab, yaitu bahwa hukum asalnya hal itu tidak membatalkan, maka ia tetap diberlakukan hingga ada dalil yang menunjukkan selain itu.
Pendapat kedua, bahwa apapun yang keluar dari selain kedua jalan itu, seperti muntah jika telah memenuhi mulut, maka ia membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Abu Hanifah.
Pijakannya adalah beberapa hadits seperti:
“Wudhu’ itu wajib untuk setiap darah yang mengalir.” (HR. Al-Daraquthni)
dan juga hadits:
“Barangsiapa yang muntah atau mengeluarkan ingus dalam shalatnya, maka hendaklah ia pergi dan berwudhu lalu melanjutkan shalatnya selama ia belum berbicara.” (HR. Ibnu Majah)
Hanya saja hadits-hadits ini didhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga mereka tidak dapat menjadikannya sebagai dalil.
Pijakannya adalah beberapa hadits seperti:
“Wudhu’ itu wajib untuk setiap darah yang mengalir.” (HR. Al-Daraquthni)
dan juga hadits:
“Barangsiapa yang muntah atau mengeluarkan ingus dalam shalatnya, maka hendaklah ia pergi dan berwudhu lalu melanjutkan shalatnya selama ia belum berbicara.” (HR. Ibnu Majah)
Hanya saja hadits-hadits ini didhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga mereka tidak dapat menjadikannya sebagai dalil.
Pendapat ketiga, bahwa apa yang keluar dari selain kedua jalan tersebut membatalkan wudhu jika ia sesuatu yang najis dan banyak, seperti muntah atau darah yang banyak. Adapun jika ia sesuatu yang suci, maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
Hujjah pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ma’dan bin Thalhah dari Abu al-Darda’ r.a., bahwa Nabi saw pernah muntah, lalu beliau berwudhu. Ma’dan berkata: “Aku pun menemui Tsauban di Masjid Damaskus lalu menyebutkan hal itu padanya. Maka ia pun berkata: ‘Engkau benar! Aku-lah yang menuangkan air wudhu beliau.” (HR. Al-Tirmidzy)
Landasan lainnya adalah pengamalan para shahabat Nabi akan hal itu, dan tidak ada satu pun yang mengingkari hal tersebut, maka dengan demikian ini adalah ijma’ dari mereka akan hal itu.
Hujjah pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ma’dan bin Thalhah dari Abu al-Darda’ r.a., bahwa Nabi saw pernah muntah, lalu beliau berwudhu. Ma’dan berkata: “Aku pun menemui Tsauban di Masjid Damaskus lalu menyebutkan hal itu padanya. Maka ia pun berkata: ‘Engkau benar! Aku-lah yang menuangkan air wudhu beliau.” (HR. Al-Tirmidzy)
Landasan lainnya adalah pengamalan para shahabat Nabi akan hal itu, dan tidak ada satu pun yang mengingkari hal tersebut, maka dengan demikian ini adalah ijma’ dari mereka akan hal itu.
Kehujahan istishhab
Para ulam usul fiqih berbeda pendapat tentang kehujahan istishhab diantaranya:
Pertama, menurut mayoritas mutakalimin (ahli kalam ), istishhab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetepkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang , harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada istishhab, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil yang lain. Istishhab menurut mereka bukan dalil. Karena menetapkanhukum yang ada di masa lampau berlangsung terus sampai masa yang akan datang.
Kedua, menurut mayoritas hanafiyyah, khususnya muta’akhirin (genarasi belakangan ), istishhab bisa menjadi hujah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan mengaggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang. Tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Alasan mereka , seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini mujtahid tersebut harus berpegang pada hukum yang sudah ada, karena dia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun demikian penetapan ini, hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku pada kasus yang akan ditetapkan hukumnya, artinya, istishhab hanya bisa dijadikan hujah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul.
Ketiga ulama malikiyyah, syafi’iyyah, hanabila, zhahiriyah dan syi’ah berpendapat bahwa istishhab bisa menjadi hujjah secara mtlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selam belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah suatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secra qath’I (pasti) maupun yang dhani (relative), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya, apabila tidak demikian maka bisa membawa akibat tidaak berlakunya seluruh hukum-hukum yang di syariatkan oleh Allh dan Rasulallah.